(Sebuah Perselingkuhan)
Oleh Denni Pinontoan
Agama, Apa Itu?
Kita sering dengan muda mendefinisikan agama hanya sebagai kumpulan dogma yang kaku, dipenuhi mitos, ritual yang seremonialistik, serta soal benar-salah dan sorga-neraka. Bahkan, negara kita Indonesia mendefinisikan agama sebagai institusi yang percaya adanya Tuhan, memiliki Kitab Suci, ada rasul, umat yang banyak dan memiliki struktur kelembagaan yang jelas. Sehingga sampai hari ini, agama yang diterima secara resmi di negara kita adalah Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Sementara sistem kepercayaan lokal, yang dalam definisi ilmu agama-agama juga sebagai agama, hanya disebut sebagai aliran kepercayaan dan kebatinan. Padahal, agama-agama lokal inilah yang pertama ada daripada negara Indonesia itu sendiri.
Kalau begitu, ternyata sudah sejak semula, dalam konteks Indonesia, agama memang telah bersinggungan secara tidak dialogis dengan kekuasaan negara. Padahal, agama (sebagai institusi) dan negara sama-sama sebagai bikinan manusia. Agama dalam konteks seperti ini akhirnya terbirokratisasi dalam kepentingan kekuasaan politik negara. Meski memang, para pendiri negara ini menyebut Indonesia bukan sebagai negara agama sekaligus juga bukan sebagai negara sekuler, tapi negara Pancasila, katanya. Tapi kenapa urusan beragama juga akhirnya menjadi urusan negara?
Kalau begitu apa agama itu? Agama menurut saya adalah sistem kepercayaan kepada yang trasendental, yang pengungkapannya antara lain berupa ritual, nyanyian, tradisi, doa-doa, yang untuk kepentingan lestarinya sistem kepercayaan itu maka dibuatlah kitab suci, doktrin dan penokohan kepada orang-orang yang dipercaya berjasa mendirikan agama tersebut. Pada mulanya, agama hadir untuk menjawab keterbatasan manusia berhadapan dengan berbagai ancaman dan tantangan hidup. Ketika bencana alam, sakit penyakit datang silih berganti, dan berbagai ancaman lainnya, maka manusia di zaman dulu mencari alternatif kekuatan untuk menjawab semua fenomena kehidupan itu. Dari sebuah kesadaran atas keterbasan diri, maka manusia kemudian mencoba mencari kekuatan diluar dirinya. Kekuatan inilah yang kemudian disebut sebagai yang Trasendental atau lazim kita menyebutnya Tuhan. Di sinilah manusia di bumi ini mulai beragama.
Beribu-ribu tahun zaman berproses, manusia kemudian menjadikan segala yang diwariskan oleh agama, misalnya kitab suci, doktrin, dan tradisi sebagai kebenaran mutlak. Manusia pun akhirnya juga menerima dengan penuh kesadaran bahwa alam, isinya dan termasuk dia, manusia, diciptakan oleh Sang Pencipta, Tuhan. Kini, miliaran penduduk dunia, hampir semua tindak-tanduk kehidupan kesehariannya sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama atau pun doktrin agama sebagai institusi. Banyak yang mempercayai nilai agama itu untuk kebaikan, baik terhadap sesama manusia maupun alam, tapi juga banyak manusia yang kemudian sadar atau tidak karena pengaruh luar biasa dari agama itu, kemudian menjadikan dia sebagai manusia pemangsa manusia lain.
Sehingga, mestinya agama yang kita kenal dan bahkan anut sekarang, harus kita lihat sebagai dua hal, yaitu sebagai sistem kepercayaan yang sifatnya personal dan sebagai institusional yang hadir di wilayah publik. Agama sebagai sistem kepercayaan yang personal, lebih menekankan pada hubungan pribadi pada oknum yang dipercayai sebagai Tuhan, yang mestinya nilai dari hubungan pribadi itu memberi isi yang positif bagi manusia dalam dia menjalani kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya, yang merupakan kenyataan disekitar hidupnya. Jadi, agama dalam hal ini terutama adalah sebagai sistem nilai yang menjadi spirit dan semangat bagi manusia untuk mengatasi berbagai tantangan dan peluang hidup.
Para pendiri agama yang kita kenal dan bahkan anut sekarang, misalnya Kristen, Islam, Budha dan Konghucu, juga pertama-tama memahami agama sebagai tindakan spiritual yang mempribadi. Yesus misalnya, tidak pernah bermaksud mendirikan agama Kristen. Yang dilakukan-Nya terutama adalah mengkritik habis-habisan perilaku atau tindakan beragama secara Yahudi. Jadi, agama Kristen didirikan pasca Yesus oleh para rasul atau orang-orang yang terinspirasi dengan ajaran dan gerakannya untuk kepentingan langgengnya ajaran dan spirit gerakan-Nya itu. Sehingga, tidak terlalu tepat juga kalau kita membedakan agama Yahudi, Kristen, Islam dengan Hindu, Budha, Konghucu sebagai agama langit dan agama bumi, agama yang turun dari langit dan agama yang didirikan manusia. Sebab, kalau kita objektif menelusuri sejarah berdirinya agama-agama yang ada, maka kita akan mendapati bahwa agama-agama itu sejatinya memang didirikan oleh manusia, dengan menggunakan Tuhan sebagai pemberi legalitas.
Sementara agama sebagai institusi, adalah agama yang berkembang belakangan pasca nilai agama itu diperkenalkan. Agama yang berkembangan kemudian ini adalah agama yang telah dilengkapi dengan struktur institusi, yang otomatis dia harus memiliki kekuasaan dan sistemnya sendiri. Di sinilah agama kemudian bersinggungan dengan publik, yang harus diperkenalkan secara struktural, mementingkan kuantitas, dan yang paling menonjol adalah usaha sentralisme kebenaran yang aksinya adalah hegemoni dan dominasi kebenaran atas yang lain. Di sinilah agama kemudian menjadi institusi sosial yang selalu berusaha tampil terbenar, tersahih dan karena itu apapun harus dilakukan, termasuk menghalalkan kekerasan.
Agama dan Kuasa Politik Negara
Negara, sejatinya adalah bikinan manusia, sebagai institusi sosial-politik besar, yang awalnya adalah untuk suatu kesejahteraan dan kebaikan. Sama dengan agama, bahwa pada mulanya negara punya maksud yang mulia dengan kehidupan manusia. Tapi, untuk mengolah negara – yang ada pendudukanya yang plural, dan batas-batas teritorialnya – maka diperlukan cara atau teknik. Cara atau teknik inilah yang belakangan kita kenal sebagai politik. Sama dengan agama dan negara, politik ternyata juga berwajah ganda, bisa untuk kebaikan bisa juga mengkibatkan keburukan bagi manusia. Karena, pada prakteknya, politik kemudian diidentikan dengan kekuasaan. Nah, kekuasaan itu sendiri, menurut definisi Max Weber, adalah kemampuan untuk mempengaruhi manusia lain untuk melakukan apa yang sebernarnya dia tidak ingin lakukan. Begitulah, sehingga saya mengatakan tadi bahwa agama juga memiliki kekuasaan, karena umat dalam agama memang dipengaruhi sedemikian rupa untuk melakukan apa yang sebenarnya tidak ingin mereka lakukan. Sejarah korupsi, menurut saya bermula dari sini. Agama, apalagi negara, sejak telah berbentuk institusi, sejatinya telah melakukan korupsi.
Sejarah panjang perjalanan agama dan negara, problem yang selalu hampir muncul adalah hubungan antara keduanya. Apakah agama harus mendominasi agama dengan sistem teokrasinya, negara mendominasi agama, atau pemisahan kedua institusi itu. Dalam sejarah Kekristenan, misalnya, reformasi Luther di abad pertengahan, terutama adalah menyoal hubungan gereja dengan negara yang saling mencari untung, dan kemudian melupakan fungsi dan perannya masing-masing untuk mensejahterakan umat atau rakyat. Di Islam sendiri, persoalan itu, sampai hari ini masih terus bergulir. Ada kelompok dalam Islam yang lebih memperlakukan Islam sebagai sistem nilai dalam negara, tapi ada juga yang melihat bahwa Islam harus menjadi acuan utama dalam kehidupan berbangsa, sehingga masih beromantisme dengan negara Islam, di peradaban lain, dan atau di waktu yang telah lampau.
Dalam konteks kita di sini dan kini, persoalannya selain persoalan saling mendominasi itu, tapi juga perselingkuhan yang tertutup atau terbuka antara agama dan kekuasaan politik. Di Sulut misalnya, ketika musim Pilkada atau Pemilu datang, ramai kita melihat bagaimana politisi berlomba-lomba menjadi orang yang tiba-tiba suci. Pra atau selama kampanye, rumah-rumah ibadah atau kegiatan-kegiatan agamawi, dengan muda kita akan bertemu dengan politisi yang berkepentingan dengan kekuasaan. Di sini yang terjadi adalah saling mencari keuntungan. Agama berharap ada pemasukan dana, sementara politisi berharap ada jaminan dukungan, atau sekedar mencari popularitas kepada publik. Agama sebenarnya sadar apa yang sedang yang dia lakukan. Dan ini agaknya menjadi cara gampang untuk memperbesar gedung rumah ibadahnya. Para alim ulamapun kadang tak tanggung-tanggun menyatakan dukungan kepada salah satu kandidat yang telah menjajikan dia setumpuk uang. Persoalan apakah si politisi itu layak menjadi pemimpin atau tidak, agaknya diabaikan dulu.
Maka, tampilan terkini dari agama-agama secara institusi itu tidak lagi bebas nilai dan indepeden, mandiri, sehingga bisa dengan leluasa menjalankan fungsinya untuk membebaskan umat dari kemiskinan struktural. Agama kemudian akhirnya hampir menjadi alat untuk melestarikan korupsi, yang menyebakan kemiskinan, kebodohan dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam keadaan seperti ini, agama kemudian lebih gampang menjadi candu bagi rakyat untuk menghilangkan kepenatan hiruk pikukknya kampanye politik kotor para elit. Sehingga jangan heran kalau agama lebih gampang mengkhotbahkan sorga dan neraka di sana yang konon itu, dari pada mengadvokasi umat/rakyat dari kemiskinan dan ketikdakdilan yang terjadi hari ini.
Ini semua terjadi karena, pertama, negara rupanya telah berhasil mempengaruhi agama sehingga menjadi lemah dan kehilangan orientasi dalam usahanya menjalankan komitmen membebaskan dan memerdekakan umatnya. Kedua, parahnya, pengaruh ini tidak kemudian diimbangi dengan perubahan paradigma berteologi dari agama-agama tersebut, yang mestinya terus melakukan evaluasi dan reinterpretasi terhadap konteks yang terus berubah, sehingga agama dapat terus memperbarui dan memperkuat diri dalam mengadvokasi umatnya berhadapan dengan berbagai tantangan persoalan hidup.
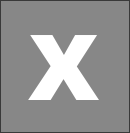






0 komentar:
Posting Komentar